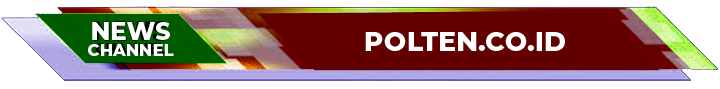Oleh: Moh. Ikhsan Kurnia, S.Sos., MBA.
Di antara deru narasi tentang digital transformation, start-up ecosystem, dan kemitraan strategis lintas negara di kawasan ASEAN, terselip kegelisahan yang nyaris senyap. Ia bukan suara dominan dalam perdebatan publik hari ini, namun hadir sebagai gema intelektual yang jernih dan membumi. Gagasan itu datang dari Kwik Kian Gie—ekonom senior Indonesia yang dalam dekade-dekade terakhir konsisten menyuarakan pentingnya keberpihakan pada ekonomi rakyat dan kewirausahaan akar rumput.
Ketika banyak ekonom melambungkan istilah growth rate, foreign direct investment, dan market liberalization sebagai penanda keberhasilan ekonomi, Kwik memilih diksi yang lain: justice, empowerment, dan resilience. Baginya, pertumbuhan ekonomi yang tak menyentuh kehidupan pelaku ekonomi kecil bukanlah kemajuan, melainkan kegagalan dalam melihat hakikat pembangunan.
Kwik tidak menolak investasi asing, juga tidak anti globalisasi. Namun ia mengingatkan dengan tegas: dalam dunia ekonomi yang kompetitif dan terbuka, negara harus hadir sebagai pelindung dan pengarah—bukan penonton pasif yang membiarkan pelaku ekonomi kecil bertarung tanpa perisai. Di sinilah letak akar pemikirannya tentang kewirausahaan: bukan sebagai kompetisi bebas semata, melainkan sebagai arena pembebasan sosial-ekonomi.
Dalam berbagai forum dan tulisan, Kwik menyuarakan kegelisahannya terhadap arah pembangunan Indonesia yang terlalu berorientasi pada kapital besar. Dalam sebuah wawancara dengan Kompas (2015), ia menyesalkan bahwa program-program liberalisasi pasar, seperti implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dilakukan tanpa strategi protektif yang memadai bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam, menurutnya, menyiapkan pelaku usahanya dengan pelatihan, insentif fiskal, dan dukungan teknologi yang konkret. Sementara UMKM Indonesia dibiarkan hidup dengan semangat, tetapi tanpa struktur penyangga yang memadai.
Kwik juga mencermati adanya structural asymmetry dalam pembangunan kewirausahaan di Indonesia. Ia melihat bahwa program-program pemerintah terlalu sering terjebak dalam retorika. Istilah seperti ekonomi digital, inkubasi bisnis, hingga enterpreneurship 4.0 menjadi jargon yang glamor, namun tak menyentuh kebutuhan paling dasar pelaku usaha: akses permodalan, keamanan regulasi, dan dukungan distribusi. Sementara itu, pedagang pasar, pengrajin lokal, atau petani kecil yang sejatinya adalah entrepreneur dalam makna esensialnya—tetap terpinggirkan dari kebijakan strategis nasional.
Kwik berangkat dari epistemologi ekonomi kerakyatan. Baginya, kewirausahaan bukan sekadar kemampuan individu menciptakan usaha, tetapi sebuah sistem nilai yang memungkinkan transformasi sosial. Ia menolak dikotomi antara kapital besar dan usaha kecil, serta menekankan pentingnya institutional scaffolding—dukungan kelembagaan yang memungkinkan pelaku ekonomi lemah berkembang secara berkelanjutan.
Pemikirannya tentang state intervention tidak bersifat populistik. Ia tak sekadar mengusulkan subsidi, tetapi membayangkan negara sebagai developmental state—yakni negara yang aktif dalam membentuk pasar, mengarahkan investasi, dan melindungi pemain domestik dari tekanan global yang tidak seimbang. Ia mengutip pengalaman Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan sebagai contoh negara yang berhasil membangun kewirausahaan nasional bukan lewat liberalisasi murni, tetapi lewat desain kebijakan industrialisasi yang visioner dan protektif.
Pemikiran Kwik terasa semakin relevan di era sekarang. Ketika euforia startup unicorn terus digaungkan, kita menyaksikan realitas lain: UMKM menghadapi digital divide, kesulitan akses pembiayaan, dan kerentanan terhadap fluktuasi pasar. Sementara negara-negara ASEAN lain memperkuat SME policy framework, Indonesia masih berkutat pada regulasi yang tumpang tindih, birokrasi yang lambat, serta minimnya keberpihakan anggaran untuk pengembangan wirausaha rakyat.
Konsep kewirausahaan yang dibayangkan Kwik melampaui logika pasar. Ia mencita-citakan inclusive entrepreneurship—yakni sebuah ekosistem kewirausahaan yang tidak elitis, tidak metropolitan-sentris, dan tidak berorientasi semata pada pertumbuhan skala, melainkan pada perluasan manfaat sosial. Dalam kerangka ini, menjadi wirausaha berarti menjadi bagian dari solusi atas ketimpangan ekonomi, bukan semata-mata pencipta profit.
Dalam konteks ASEAN, kegelisahan Kwik juga menyentuh wilayah geopolitik ekonomi. Ia mengingatkan bahwa liberalisasi regional tidak netral. Negara yang tidak siap secara institusional akan menjadi korban dari arus barang dan jasa lintas negara. Ia mengkritik keras kebijakan pembukaan pasar tanpa capacity building yang memadai, serta memperingatkan bahwa “MEA dapat menjadi jalan mulus bagi produk asing menguasai pasar domestik, sementara pelaku usaha lokal kita belum memiliki daya saing struktural.”
Peringatan ini bukan sinisme, melainkan kehati-hatian yang lahir dari pengalaman panjang dalam pemerintahan dan observasi empiris terhadap berbagai kegagalan pembangunan. Kwik adalah contoh ekonom yang tidak takluk pada dogma pasar, tetapi juga tidak tenggelam dalam romantisme proteksionisme. Ia berdiri di tengah sebagai pragmatic realist—mengusulkan desain pembangunan kewirausahaan yang berdimensi sosial, ekonomi, dan kultural.
Kini, saat dunia memasuki era post-globalization dengan disrupsi teknologi dan ketegangan geopolitik yang meningkat, kita dihadapkan pada pertanyaan mendasar: model kewirausahaan seperti apa yang hendak kita bangun? Apakah kita akan terus mengejar unicorn economy dan mengagungkan inovasi teknologi tanpa fondasi sosial? Ataukah kita bersedia membangun ekosistem yang memberdayakan petani, nelayan, pengrajin, dan pelaku ekonomi informal—sebagai subjek utama pembangunan ekonomi nasional?
Pemikiran Kwik Kian Gie mengajak kita untuk kembali menata ulang prioritas. Ia mengingatkan bahwa di tengah ketidakpastian global, bangsa yang kuat adalah bangsa yang berpijak pada kekuatan internal: pada rakyat yang mampu berdikari secara ekonomi. Dan dalam dunia yang semakin terfragmentasi, konsep kewirausahaan kerakyatan yang inklusif bisa menjadi jangkar moral sekaligus strategi pembangunan jangka panjang.
Kita boleh mengimpor teknologi, mempelajari model bisnis asing, dan membuka pintu investasi. Tetapi kita tak boleh kehilangan soul dari kewirausahaan itu sendiri: yaitu keberanian untuk menciptakan, ketekunan untuk bertahan, dan keberpihakan pada sesama. Dalam kerangka inilah, gagasan Kwik bukan hanya warisan intelektual, tetapi juga panduan etik bagi arah kewirausahaan Indonesia ke depan.
*Penulis adalah Dosen Kewirausahaan Universitas BTH & Direktur Kemitraan Perkumpulan Program Studi Kewirausahaan Indonesia (APSKI); Pemerhati Kewirausahaan Asia Tenggara.